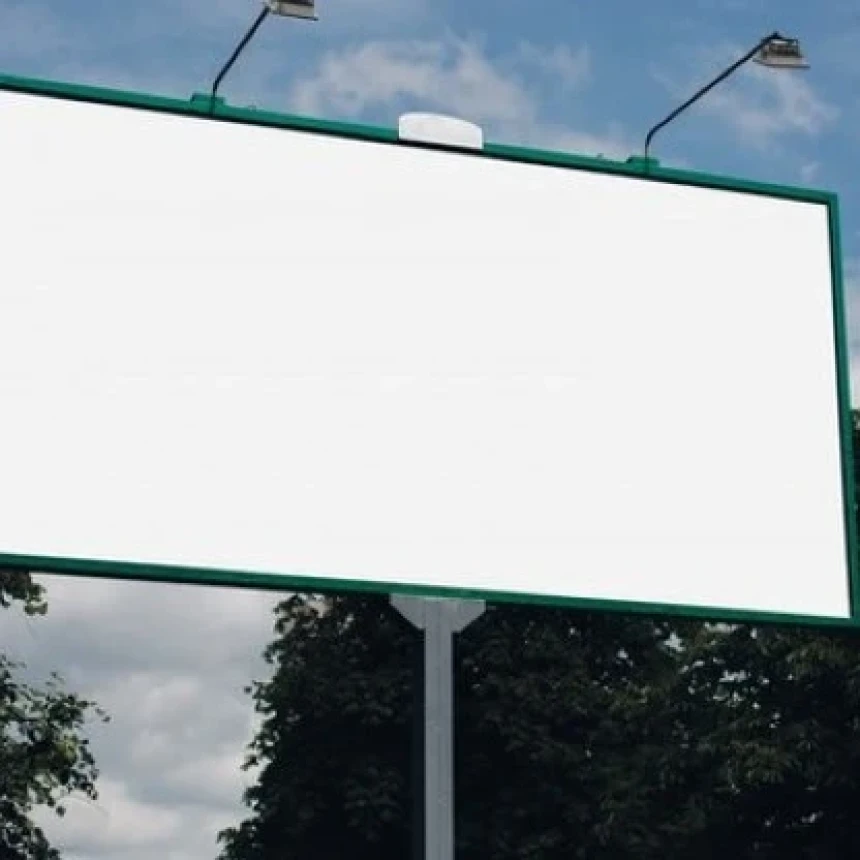Cerpen: E. Rokajat Asura
Aku sering kali tak enak hati karena pada akhirnya Kang Gundil dijadikan contoh untuk sesuatu yang buruk. Saat ada anak-anak nakal, tak bisa mengaji, pengangguran, lalu masyarakat cukup menyebutnya "Dasar Gundil." Aku yakin benar– mudah-mudahan Gusti Allah melindungi mereka–bahwa kedua orang tua Kang Gundil tak pernah mengharapkan anaknya bernasib buruk. Bukankah seorang perampok saja tak pernah menginginkan anaknya menjadi perampok? Wa Salman almarhum pernah bicara padaku, Kang Gundil diberi nama seperti itu karena semata-mata mengejar perhitungan repok agar jatuh pada angka yang baik.
Suatu kali Kang Gundil bilang: "Doakan Pak Guru (dia selalu memanggilku demikian) saya sedang mencari Tuhan." Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi ketika dia mengatakan harus mengenal dan bersahabat dengan bumi dan malaikat agar tidak mengalami siksa kubur, mau tidak mau aku menanggapinya dengan serius.
"Kenapa harus begitu, Kang?"
"Lho, Pak Guru ini gimana? Bumi itu harus dianggap saudara, sebab seasal, sedarah, hanya berbeda wujud saja. Karena seasal dan sedarah, saya harus mengenalnya lagi agar nanti bisa bersahabat."
"Iya, Kang, kita memang harus mengenal dan bersahabat tidak saja dengan bumi, tetapi dengan seluruh isi bumi."
Baca Juga
Depresi
Kang Gundil menatap tajam, lalu pergi begitu saja, tanpa pamit. Barangkali sikapnya yang demikian itulah, kenapa masyarakat di kampung kami menilainya sebagai orang tak tahu adab, bahkan tak sedikit yang mengira Kang Gundil sinting. Emak pernah bilang sebenarnya dulu Kang Gundil termasuk anak shaleh, gampang disuruh, kerjanya rajin sehingga semua orang menyenanginya. Tapi entah kenapa ketika menginjak usia dewasa, dia mulai berubah.
Menjelang maghrib ketika aku pulang mengajar dari madrasah, aku melihat Kang Gundil duduk di warung menikmati penganan. Aku bisa menangkap suasana kontras di warung saat itu, antara Kang Gundil yang senang dan wajah Bi Emi – pemilik warung yang tak ramah. Aku pernah mendengar, setiap Kang Gundil jajan tak pernah mau bayar. Kalaupun dipaksa, dia teriak-teriak, katanya tukang warung kikir, tak mau mengeluarkan sebagian hak orang miskin.
"Mampir, Pak Guru!" Bi Emi mempersilakan aku masuk. Aku hanya mengangguk karena sebenarnya tak ada niatan mampir. Kang Gundil terlihat mengerling, sebelah tangannya memasukkan goreng tape yang tersisa, lalu ngeloyor pergi. Sebelum tukang warung mencak-mencak, aku menyodorkan sejumlah uang yang menurutku kira-kira cukup untuk membayar apa yang telah dimakan Kang Gundil sore itu.
***
"Buka, Pak Guru! Cepat buka!" teriak dari luar.
"Siapa?”
Baca Juga
Naik Kelas
"Gundil, Pak Guru! Gundil. Terima kasih tadi sore sudah ditraktir…"
Darahku deras mengalir, dingin dan semakin tidak mengerti. Dari mana dia tahu kalau aku telah mentraktirnya? Bukankah sebelum aku membayar tadi, dia telah lebih dahulu pergi?
"Pak Guru."
"Sebentar, Kang."
Jendela kubuka, Kang Gundil berdiri dengan tatapan khasnya, tajam dan menelanjangi.
"Aku bertemu Gusti Allah," katanya kemudian, sama sekali tak menyiratkan dia sedang bercanda. Lalu dia bicara panjang lebar, dia bisa melihat Gusti Allah pada batu, pada gunung, pada pohon, di hamparan sajadah, di puncak masjid dan pada hati orang yang selalu berdiri merendah di hadapan-Nya. Dia mengaku percuma hidup untuk manusia atau hidup untuk dunia, karena manusia akan mati dan dunia akan hancur.
"Bagaimana persahabatan dengan bumi dan malaikat?"
"Pak Guru ini bagaimana? Justru karena saya sudah mengenal dan bersahabat dengan bumi, saya harus meninggalkannya," sergah Kang Gundil.
"Kita ngobrol di dalam ya, Kang."
Baca Juga
Surat untuk Kusrin
Kang Gundil menggeleng.
"Memangnya Akang nggak pegal?"
"Aku tak akan pegal tanpa dipegalkan pemilik rasa pegal itu, Guru," katanya kemudian. Aku mengingatkan dia agar jangan sampai asal ngomong, bisa dicap macam-macam. Kang Gundil tertawa dan mengatakan kalau aku ini kerdil, tak punya keberanian hanya untuk mengatakan yang benar itu benar. Padahal katanya, aku ini seorang guru, jadi panutan sekian banyak anak dan orang tuanya. Aku dibuatnya diam.
"Seperti Pak Guru, setelah mengenal dan bersahabat dengan bumi, saya juga akan mengenal dan bersahabat dengan malaikat," katanya kemudian.
"Ah…Akang ini. Saya ini hanya seorang guru, Kang."
"Tanpa melihat pun saya tahu karena punya hati, yang tidak memerlukan jarak, sekalipun terhalang gunung dan samudera, hati pasti bisa melihatnya dengan sangat jelas, seperti sore tadi Pak Guru mentraktir saya."
Lagi-lagi aku hanya tersenyum.
"Kenapa Pak Guru tersenyum? Kalau Pak Guru tidak sepaham kemudian tersenyum, sama saja dengan mengerdilkan saya. Pak Guru ini bercabang. Selama ini Pak Guru satu-satunya di kampung kita ini yang tak pernah menghina saya."
"Maaf, Kang, saya tidak bermaksud menghina. Saya hanya ingin mengingatkan kalau tata krama dan adab itu sangat penting. Coba kalau selama ini Akang memakai tata krama, pasti tidak akan kena marah dan dituding macam-macam. Sekalipun apa yang Akang katakan kalau dalam harta kita itu ada hak orang lain."
"Baiklah, saya percaya. Soal tata krama dan adab itu, Pak Guru saja yang katakan pada mereka. Saya ini bukan tidak tahu tata krama, tapi tidak mau memakai tata krama yang mereka anggap benar. Kalau setiap jajan saya tidak bayar, tidak bermaksud mencuri tapi untuk mengambil hak fakir miskin yang ada pada harta-harta mereka. Assalamualaikum," katanya terus ngeloyor membiarkan aku didera bengong.
Baca Juga
Kambing Jantan Bergigi Poel
Kang Gundil terus melangkah, lalu hilang ditelan kegelapan. Aku masih tetap berdiri sampai benar-benar merasa saatnya untuk menutup kembali jendela kamar. Aku tak mengira kalau malam itu terakhir bertemu Kang Gundil. Pagi-pagi benar suasana kampung seketika ramai ketika ditemukan mayat Kang Gundil di pinggir sungai. Aku hanya mematung dan kembali teringat kata-kata Kang Gundil tadi malam. Aku merasa terpanggil untuk untuk menyampaikan apa yang diamanatkan Kang Gundil.
Selama beberapa hari kami terus membicarakan Kang Gundil. Polisi berencana mengusut kematiannya, menggali kembali kuburnya untuk kepentingan otopsi. Tapi pihak keluarga tak menyetujuinya. Biarlah dia tenang dan tidak diributkan dengan sangkaan-sangkaan jelek, katanya.
Setelah selesai tahlilan aku iseng menceritakan obrolan kami malam itu. Tak ada seorang pun yang percaya kalau sesungguhnya almarhum telah menemukan hakikat hidup. Namun tak ada seorang pun yang menyangka jelek, tak ada yang menuduh bunuh diri misalnya.
"Gundil telah diambil oleh kuasa-Nya dalam keadaan senyum, betapa damai dia menghadapi kematian yang ditakuti semua orang itu. Sepertinya Gusti Allah sangat menyayanginya sehingga ridha mengakhiri kematian seorang makhluk-Nya ini dengan senyum," cerita Ustadz Adang ketika selesai memimpin acara tahlilan.
"Justru saya sendiri seperti sedang mimpi, Ustadz, saya bertemu almarhum di depan jendela kamar," kataku mengulang kisah malam itu dengan almarhum.
"Memangnya kenapa, Guru?"
Aku ceritakan semuanya, tanpa yang terlewat. Mendengar ceritaku itu Ustadz Adang hanya mengangguk. Dia kemudian menjelaskan bahwa salah satu tanda orang yang ridha meninggalkan dunia ini akan diberi kesempatan bertemu dengan seseorang yang dianggap dapat menyampaikan amanatnya kelak, terutama mewasiatkan sesuatu yang penting untuk kemaslahatan kehidupan.
Aku dan juga Ustadz Adang sama-sama masih bingung menyikapi kehidupan Kang Gundil. Keesokan harinya pagi-pagi benar Ustadz Adang datang ke rumah dan mengajaknya ke halaman belakang meminta ditunjukkan di mana malam itu Kang Gundil berdiri. Tanpa menaruh curiga apa-apa, aku mengantarnya.
Sesampai di halaman belakang, aku terkesiap, tepat di bawah jendela tempat terakhir kali Kang Gundil berdiri, aku menemukan pohon bunga tumbuh subur. Entah siapa yang menanamnya di sana, hanya yang jelas bunga itu harum sekali. Aku sendiri tak pernah menanam bunga di halaman belakang apalagi di bawah jendela itu.
"Di mana malam itu almarhum berdiri, Guru?"
Baca Juga
Mobil Tua
"Ya, di sini, di tempat tumbuhnya bunga ini, Ustadz."
"Masyaallah." Ustadz Adang berjongkok mencium bunga itu. Di samping bunga tak terlihat tanah berceceran yang menandakan bekas menanam bunga itu.
"Siapa yang menanam bunga ini?"
"Itulah yang membuat saya kaget, Ustadz. Tak pernah ada yang menanam bunga itu, nama bunganya saja tidak tahu."
Mendengar penjelasanku, Ustadz Adang kembali tersenyum. Entah apa arti senyuman itu, hanya yang jelas saat itu juga dia melantunkan doa untuk Kang Gundil.
"Maha benar Allah yang telah memberikan satu tanda lagi bagi umat yang berpikir," ujar Ustadz Adang setelah selesai berdoa. Aku sendiri tetap saja bingung, apa sesungguhnya yang telah terjadi. Ketika hal itu aku tanyakan pada Ustadz, kembali dia hanya tersenyum. Senyum yang terus diselimuti misteri.
***
E Rokajat Asura, lahir di Bandung. Telah banyak memperoleh penghargaan dalam menulis. Belakangan lebih mengkhususkan diri dalam menulis novel sejarah atau berlatar belakang sejarah. Novel Dwilogi Prabu Siliwangi merupakan novel sejarah pertama yang laris di pasaran. Novel Kupilih Jalan Gerilya (novel biografi Panglima Besar Sudirman), yang terbit tahun 2015, mengantarkan ke Ubud Writers and Readers Internasional Festival 2016 di Ubud, Bali, dan dipresentasikan dalam diskusi panel bertajuk Past & Present bersama penulis lain dari Meksiko, Amerika, Inggris dan Australia. Novel Raden Pamanah Rasa, telah diproduksi sinetron serial dengan judul sama dan tayang di RCTI. Beberapa buku yang terbit tiga tahun terakhir antara lain Haji Hasan Mustapa: Sufi Besar dari Tanah Pasundan (Biografi, Imania, 2020), Budak Angon: Kiprah M. Ridwan Kamil (Biografi, Biro Adpim Sekda Jabar, 2021), Halimun di Cikertawana (Kumpulan Cerpen, Sibera, 2022), Senandung Cinta dari Pesantren (Antologi Cerita Pendek, Diva Press, 2022), Reuni Alumni Munsi III (Kumpulan Puisi, Cerita Pendek, dan Esai, Sibera, 2022). Puisinya dipublikasikan dalam Mengenang Sang Penjaga H.B Jassin (Antologi Komunitas H.B Jassin 2021-2022 Angkatan Milenial, Teras Budaya, 2022), Napak Jaman (Kumpulan Carita Pondok Pasanggiri Ngarang Carpon Pakarangan 2022, Humasastra, 2022), Tien (Novel biografi Siti Hartinah Soeharto, Sibera, 2023), Cerita-Cerita Senja (Kumpulan Cerpen tentang Kerafian Lokal Para Pengarang Munsi III, Sibera, 2023) dan Anjang-anjangan (Novel Sunda, Sibera, 2023).
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi dan 4 Sifat Teladan Rasulullah bagi Para Pemimpin
2
Tata Cara Shalat Gerhana Bulan, Lengkap dengan Niat dan Surat yang Dianjurkan
3
Khutbah Jumat: Menjaga Amanah dan Istiqamah dalam Kehidupan
4
Khutbah Jumat: Merawat Keutuhan Keluarga di Era Media Sosial
5
Lusa, Umat Islam Dianjurkan Puasa Ayyamul Bidh Rabiul Awal 1447 H, Berikut Niatnya
6
Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat, DPR Stop Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunjungan ke Luar Negeri
Terkini
Lihat Semua