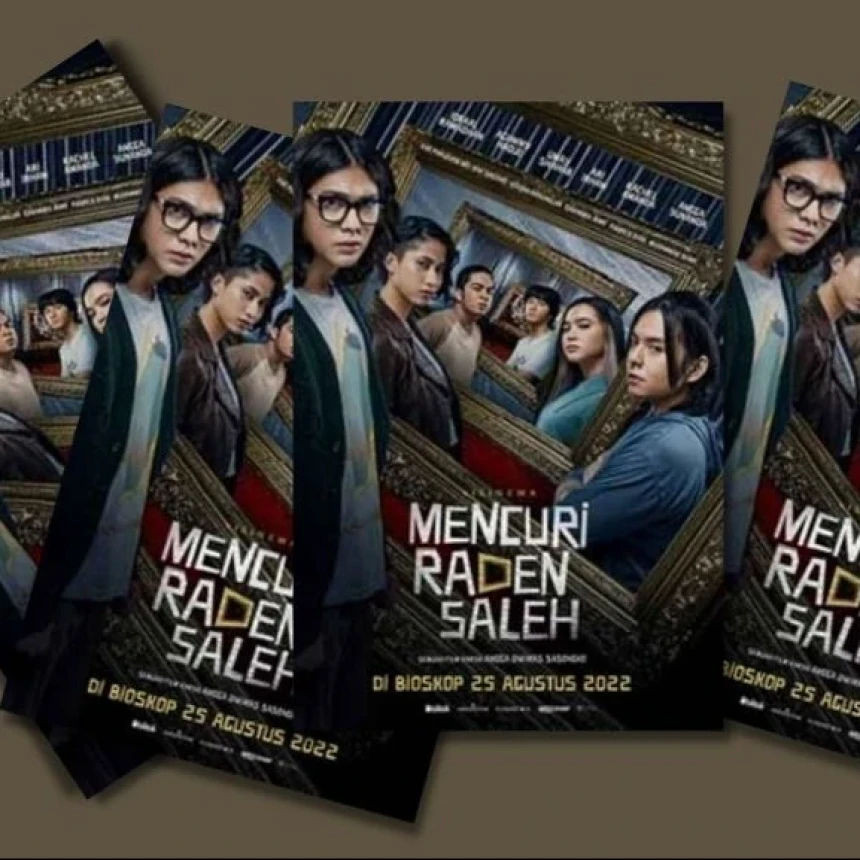Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media
Jumat, 22 Agustus 2025 | 14:31 WIB
Di tengah hiruk pikuk festival budaya Pacu Jalur di Kuantan Singingi, Riau, di antara sekian banyak penari Pacu Jalur, seorang anak laki-laki menjadi pusat perhatian. Ia menari dengan penuh semangat di depan perahu panjang, mengikuti irama ombak sungai, diiringi oleh para pendayung dan sorak sorai penonton. Tarian ini menjadi viral dan menjadi tren di media sosial. Gerakan tariannya diikuti oleh semua orang, mulai dari masyarakat umum, atlet ternama, selebritas Instagram, YouTuber, hingga pejabat, politisi, bahkan polisi.
Penari Pacu Jalur muda ini bernama Dika. Tariannya dengan cepat menjadi viral. Klip pendeknya tersebar luas di TikTok, Instagram, dan YouTube, berhasil menembus batas wilayah, menarik banyak pengguna media sosial dari berbagai negara, termasuk negara-negara Eropa. Netizen dari seluruh Indonesia terkesima dengan acara yang menjadi tren global ini bahkan kemudian Dika diundang hadir mengisi hiburan dalam momen pengibaran bendera di perayaan Hut RI ke-80 di Istana Negara.
Ada hal menarik untuk disimak dari fenomena ini, apa sebenarnya yang terjadi di balik pusaran viralitas ini? Apakah sekadar hiburan ringan untuk mengisi waktu, ataukah ada fenomena komunikasi budaya yang lebih kompleks dan penting? Mengapa konsep "aura farming", praktik memanen atensi digital, menjadi kunci untuk memahami dinamika yang terjadi?
Viralitas tarian Dika bukan sekadar fenomena viralitas media. Tarian ini menjadi cerminan tajam dari benturan dan negosiasi antara logika komunikasi budaya tradisional yang kaya makna dan logika algoritma media digital yang digerakkan oleh ekonomi atensi. Benturan ini barangkali memunculkan praktik "aura farming", yang, meskipun memberikan peluang untuk terekspos, menimbulkan pertanyaan kritis tentang potensi eksploitasi, esensi pelestarian, dan nasib makna budaya di ruang publik digital yang serba cepat.
Pacu Jalur, Identitas, Budaya, Nilai, dan Komunitas
Pacu Jalur sendiri, menilik dari berbagai sumber, dapat kita pahami secara sebagai suatu budaya yang merupakan tradisi tahunan yang berakar kuat dalam budaya masyarakat Kuantan Singingi. Kompetisi dayung perahu panjang ini bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan ritual budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semangat kolektif, gotong royong, kehormatan, dan warisan sejarah, semuanya terjalin dalam jalinan tersebut.
Festival tahunan ini, yang biasanya diadakan di Sungai Kuantan selama Hari Kemerdekaan Indonesia, sarat dengan nilai-nilai dan ritual sakral. Terdapat prosesi mandi jalur, doa (membaca doa selamat), dan penghormatan mendalam kepada leluhur. Pacu Jalur sendiri merupakan puncak kekuatan fisik, kekompakan tim (biasanya 40-60 pendayung ditambah penari dan juru mudi), dan semangat sportifitas yang tinggi antardesa atau kecamatan. Anak-anak tentu saja merupakan bagian dari tradisi ini, tetapi peran mereka lebih pada berpartisipasi dalam prosesi, menyaksikan dengan takjub, atau secara bertahap mempelajari nilai-nilai leluhur.
Mereka bukanlah penari utama, yang berdiri sendiri di jalur selama perlombaan, seperti Dika. Komunikasi budaya dalam Pacu Jalur tradisional bersifat komunal, ritualistik, sarat makna mendalam, dan bertujuan untuk memupuk solidaritas internal masyarakat serta penghormatan terhadap warisan.
Dalam konteks ini, Dika lebih dari sekadar penari cilik. Ia adalah bagian dari atmosfer budaya yang dinamis. Tarian spontan di tengah berlnagsungnya tradisi ini merupakan ekspresi keterikatan emosional, tradisi, dan identitas lokal. Namun, begitu aksinya terekam dan videonya hadir di media sosial, maknanya dapat berubah. Tarian Dika terlepas dari konteksnya dan menjadi tontonan yang merepresentasikan wajah budaya yang dikonsumsi oleh penonton yang tidak selalu memiliki hubungan langsung dengan budaya asalnya.
Dari Tradisi yang Meraih Perhatian, Cuplikan Budaya yang Menembus Dunia
Saat ini, kita hidup dalam sebuah era di mana apa pun bisa menjadi konten, dan semua konten bersaing untuk mendapatkan perhatian. Ketika video Dika diunggah ke TikTok, video tersebut langsung tersedot ke dalam logika algoritma yang menilai popularitas berdasarkan interaksi seperti suka, komentar, bagikan, dan waktu tonton yang cepat meningkat. Budaya lokal, yang dulu hanya hadir di ruang komunitas fisik, kini beranjak ke panggung digital global.
Inilah proses mediasi budaya, tradisi tidak lagi hadir sebagai pengalaman sakral dari komunitas yang melestarikan, melainkan sebatas sebagai tontonan. Tradisi-tradisi tersebut dikemas ulang, dipotong, diberi keterangan humor atau dramatis, disisipkan dengan musik latar yang sedang tren, dan diunggah ulang oleh berbagai akun. Budaya menjadi "konten yang relevan". Pacu Jalur bukan lagi tentang masyarakat Kuansing yang mendayung bersama untuk melestarikan budaya Pacu Jalur, melainkan tentang gerakan tari seorang anak laki-laki yang menari di ujung depan sampan Pacu Jalur.
Pada titik tersebut, video Dika menjadi menarik, dan logika komunikasinya dapat berubah secara dramatis. Konsep "aura farming" menjadi lensa krusial. Dalam ekosistem digital, "aura farming" mengacu pada praktik memanen atau menarik perhatian ("aura") melalui konten yang dirancang atau, seringkali, seperti dalam kasus Dika, diciptakan secara spontan untuk memicu respons emosional yang kuat (hiburan, kekaguman, antusiasme, kesedihan, humor, keanehan, atau kontroversi). Hal ini kemudian dapat meningkatkan interaksi, suka, bagikan, komentar, tayangan, dan bahkan imitasi tindakan. "Aura" inilah yang menjadi mata uang baru dalam ekonomi perhatian.
Aura Farming dan Ekonomi Perhatian
Pertanyaannya adalah, apa yang membuat video Dika begitu menarik? Beberapa orang mungkin menyebutnya lucu, menggemaskan, unik, dan menghibur. Namun, lebih dalam dari itu, kita menyaksikan apa yang dikenal sebagai "aura farming", sebuah praktik memanen keaslian, emosi, dan spontanitas untuk menarik perhatian di dunia digital. Istilah ini merujuk pada fenomena di mana pengalaman atau ekspresi yang dianggap "asli" diubah menjadi komoditas emosional.
Dika menari riang. Tanpa naskah, tanpa skenario, tanpa ambisi menjadi selebritas Instagram. Ia tampil sebagai dirinya sendiri, di tengah budaya yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun begitu rekaman memasuki ruang digital, segalanya bisa berubah. Tarian Dika menyentuh emosi banyak orang karena tidak dipentaskan.
Namun justru karena keasliannya, video tersebut menjadi lahan subur bagi para kreator, akun viral, bahkan pejabat dan politisi yang ingin melewatkan momen tersebut. Ia menjadi bagian dari ekonomi perhatian, di mana konten yang menarik perhatian memiliki nilai tukar yang tinggi.
Dalam logika ini, komunikasi bukan lagi sekadar menyampaikan pesan, melainkan menciptakan dan mengeksploitasi afeksi. Setiap share, like, dan repost bukan sekadar tindakan konsumsi, melainkan produksi nilai, bagi akun yang mengunggahnya, bagi algoritma, dan bahkan bagi pasar yang mulai memperhatikan "influencer lokal" baru.
Baca Juga
Media Sosial dan Pusaran Kebencian
Representasi dan Relasi Kuasa
Insiden viral Dika bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan merupakan gejala dari dinamika komunikasi budaya yang lebih luas di era digital. Di tengah arus platform digital yang digerakkan oleh algoritma dan ekonomi atensi, budaya lokal yang seharusnya kaya makna dan konteks justru semakin direduksi menjadi konten mentah.
Tradisi sakral dan kompleks, seperti Pacu Jalur, direduksi menjadi visual yang mudah dicerna, cepat, emosional, dan layak viral. Narasi dan kedalaman filosofis yang menyertainya terpinggirkan oleh godaan untuk meraup perhatian dari emosi instan demi pertukaran ekonomi. Dalam kecepatan distribusi konten digital yang terfragmentasi, narasi yang seharusnya menjelaskan sejarah, nilai, dan proses komunal tradisi-tradisi ini justru terpinggirkan dalam gelombang video dan foto lengkap dengan lagu-lagu remix dan teks humor.
Kita terlalu sering berasumsi bahwa viralitas adalah bentuk pengakuan. Padahal, viralitas bisa jadi merupakan bentuk melupakan sakralitas esensinya. Budaya tidak ada secara utuh, melainkan dalam potongan-potongan kecil. Yang penting adalah menghibur, membuat orang tertawa, terharu, atau membuat heboh di FYP. Dan kita semua, tanpa disadari, menjadi bagian dari elemen dalam siklus digital ini.
Fenomena ini menciptakan pertarungan narasi yang tidak seimbang, siapa yang benar-benar memegang kendali? Apakah masyarakat Riau pemilik budaya, ataukah algoritma, kreator konten, dan khalayak urban yang hanya mengamati dari kejauhan dan menilai dari cuplikan belaka? Di manakah suara autentik masyarakat lokal dalam pusaran ini?
Ironisnya, dalam kondisi seperti ini, fenomena seperti yang dialami Dika dapat dibaca sebagai strategi bertahan hidup yang tak terelakkan, budaya lokal dipaksa untuk "berkomunikasi" dengan cara yang sesuai dengan logika digital demi mendapatkan perhatian. Ini adalah bentuk "aura farming", sebuah upaya yang hampir tak disadari untuk mempertahankan eksistensi budaya melalui eksploitasi citra autentik, meskipun dengan risiko distorsi makna yang cukup signifikan.
Viralnya tarian Dika dalam perayaan Pacu Jalur di Riau bukanlah fenomena tanpa konteks. Hal ini mencerminkan bagaimana budaya lokal dikonsumsi dalam logika digital yang cepat, dangkal, dan emosional. Dalam menanggapi fenomena viralitas Dika dan reduksi budaya Pacu Jalur menjadi konten instan, kita tidak bisa begitu saja mengeksploitasi viralitas atau meromantisasi tradisi. Sebaliknya, kita perlu menemukan jalan tengah yang kritis, dengan mengakui bahwa viralitas membuka peluang untuk terpapar budaya lokal yang sebelumnya tidak dapat diakses, sekaligus menyadari potensi distorsi dan eksploitasi makna budayanya.
Ini bukan soal memilih antara hitam dan putih, melainkan membaca nuansa abu-abu, yang membutuhkan kepekaan budaya dan literasi digital yang lebih tinggi. Baik bagi kreator maupun konsumen konten, memahami konteks di balik konten viral sangatlah penting. Terutama ketika melibatkan anak-anak, kehati-hatian dan penghormatan terhadap sakralitas esensi budayanya menjadi sangatlah penting.
Momentum viralitas Dika harus dimanfaatkan secara positif, menjadi titik awal untuk memperkenalkan Pacu Jalur (dan berbagai budaya lainnya) secara lebih substansial. Kolaborasi etis antara pemerintah daerah, komunitas budaya, kreator konten, dan sektor pariwisata dapat menjadikan tradisi dan kebudayaan Indonesia lainnya dikenal luas tanpa kehilangan sakralitasnya, bukan sekadar sumber perhatian sesaat, melainkan bagian dari perjumpaan yang mendalam dan berkelanjutan.
Kita perlu ingat bahwa budaya bukan hanya sekadar warisan, tetapi ia harus dilestarikan. Bukan sekadar hiburan tetapi dia hidup, berkembang, dan memiliki nilai-nilai yang lebih besar daripada sekadar viralitas di media sosial. Jadi, mari kita menari bersama di media dengan tetap memegang sakralitas budaya, dengan penuh kesadaran. Menari dengan pemahaman, bukan sekadar terhanyut oleh algoritma dan mengikuti arus viralitas media.
Mahbub Ubaedi, penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia