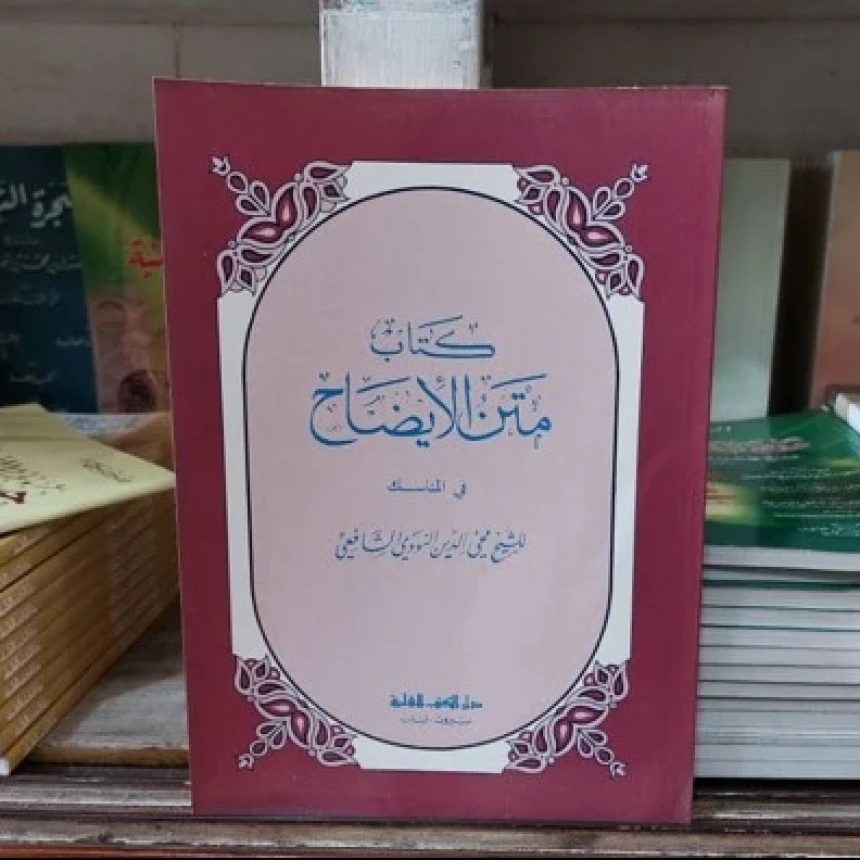Agung Purnama
Kolomnis
Setibanya di Tanah Air, Muslim yang telah melaksanakan ibadah haji, di depan namanya akan segera tersemat gelar “haji”. Tidak lupa, gaya berpakaian pun sedikit berubah, sesekali bersurban, bergamis, atau kalau memakai penutup kepala dapat memakai “kopiah haji”.
Dalam konteks sejarah, tepatnya pada masa Hindia Belanda, penggunaan "gelar haji" dan “berpakaian haji” harus melewati screening yang ketat dari pemerintah. Semisal peraturan yang tertuang dalam Staatsblad nomor 42 tahun 1859.
Dalam buku De Islam en Zijn Beteekenis voor Nederlands Indie, disebutkan bahwa aturan tersebut mewajibkan jamaah haji harus mengajukan permohonan izin perjalanan sebelum berangkat, serta pemberitahuan ketika sudah pulang. Izin diajukan kepada bupati setempat. Selanjutnya, para bupati diinstruksikan untuk menguji para jamaah haji yang telah kembali.
Baca Juga
Mengenang Misi Haji Pertama Indonesia
Ujian ini semacam penyelidikan apakah mereka benar-benar mengunjungi Tanah Suci atau tidak. Jika ternyata benar, peserta ujian dapat menerima sertifikat (Spat 1925, 48). Aturan lainnya juga disyaratkan bagi calon haji. Mereka harus membuktikan kepada bupati bahwa ia mempunyai biaya yang cukup untuk perjalanan pulang-pergi, serta memiliki biaya untuk keluarga yang ditinggalkan.
Kalau lulus dari pengujian ini, jamaah haji diperkenankan memakai gelar serta boleh berpakaian haji (Vredenbregt 1962, 100).
Tidak sekadar screening secara ketat, pada tahun 1872 seorang Residen Surabaya bernama van Deventer (menjabat 1868-1873) bahkan sampai menetapkan aturan pelarangan pakaian Arab atau “pakaian orang yang sudah melaksanakan haji.” Ia mengusulkan agar pemerintah Hindia Belanda memperketat pemisahan antaretnis dan bangsa sehingga masing-masing dipaksa memakai cara pakaian bangsa dan etnisnya, semisal orang China dengan rambut yang dikepang, orang Arab dengan surban dan jubahnya, orang Jawa dengan blankon dan surjan luriknya, dan yang lainnya.
Terkait hal ini, seorang Adviseur voor Inlandsche Zaken (pejabat penasehat urusan pribumi) bernama Karel Frederick Holle (1829-1896) merespons usulan ini dengan keberatan. Ia menolak pelarangan pakaian haji, karena larangan tersebut justru akan menimbulkan kegelisahan dan protes masyarakat pribumi.
Menurut Holle, pakaian haji ini juga tidak seragam; di beberapa daerah memang kebanyakan mirip pakaian gamis Arab, namun di daerah lain ada yang hanya surban saja. Di Tatar Sunda, tempat Holle bekerja, pada waktu itu banyak pemimpin agama dan para jamaah haji yang memakai jas potongan mode Eropa sebagai pakaian khas haji (Steenbrink 1984, 237-238).
Sementara itu, seorang ilmuwan populer Belanda, yang juga seorang Adviseur voor Inlandsche Zaken bernama Snouck Hurgronje (1857-1936) mengamini pendapat Holle. Ia beranggapan apa yang dimaksud pakaian haji tidak lah seragam dan tidak ada model bakunya.
Snouck mengkritik keras peraturan tahun 1859 dan menyatakan bahwa gelar serta pakaian haji tidak perlu diatur, dan bahwa pembatasan ibadah haji apa pun akan berdampak sebaliknya dari keuntungan yang diharapkan pemerintah (Vredenbregt 1962, 100).
Lebih dari itu, Snouck bahkan mengusulkan agar gelar dan pakaian haji tersebut dibebaskan untuk dipakai oleh siapa saja. Maksudnya, kalau sudah digunakan dan dipakai oleh masyarakat umum, gelar dan pakaian haji tidak akan lagi menjadi sesuatu yang istimewa. Jadi pemerintah pun tidak perlu mengawasi secara khusus.
Terkait yang terakhir ini, Holle tidak sependapat dengan Snouck. Baginya, pakaian haji tidak perlu dilarang tapi jangan juga terlalu dibebaskan menjadi milik umum. Sebagai pegiat, peneliti, dan pecinta budaya Sunda, Holle khawatir kebudayaan dan corak khas Sunda akan hilang jika semua orang diizinkan memakai pakaian kearab-araban.
Holle malahan memiliki usulan yang agak nyeleneh. Dia menganjurkan agar seragam opsir-opsir Belanda dibuat kearab-araban. Tujuannya, agar timbul kebencian terhadap pakaian Arab, sebagaimana kebencian terhadap aparat Belanda yang berseragam pakaian tersebut (Steenbrink 1984, 242–43).
Kritik-kritik dari para ilmuwan seperti Holle dan Snouck tidak membuat pemerintah mau mengubah peraturan yang sudah ada. Gubernur Jenderal Hindia Belanda tetap memutuskan bahwa yang boleh menggunakan gelar “haji” dan memakai “pakaian haji” hanya lah mereka yang lulus pengujian oleh bupati terkait haji (Steenbrink 1984, 243). Meskipun kemudian, seiring bertambahnya jumlah jamaah haji, aturan pengujian dalam peraturan nomor 42 tahun 1859, dihapuskan pada tahun 1902 (Spat 1925, 48).
Agung Purnama, Pengurus Lakpesdam NU Jawa Barat dan dosen tetap Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi dan 4 Sifat Teladan Rasulullah bagi Para Pemimpin
2
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
3
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
4
Pengacara dan Keluarga Yakin Arya Daru Meninggal Bukan Bunuh Diri
5
Khutbah Jumat: Menjaga Amanah dan Istiqamah dalam Kehidupan
6
Gus Yahya Ajak Warga NU Baca Istighfar dan Shalawat Bakda Maghrib Malam 12 Rabiul Awal
Terkini
Lihat Semua